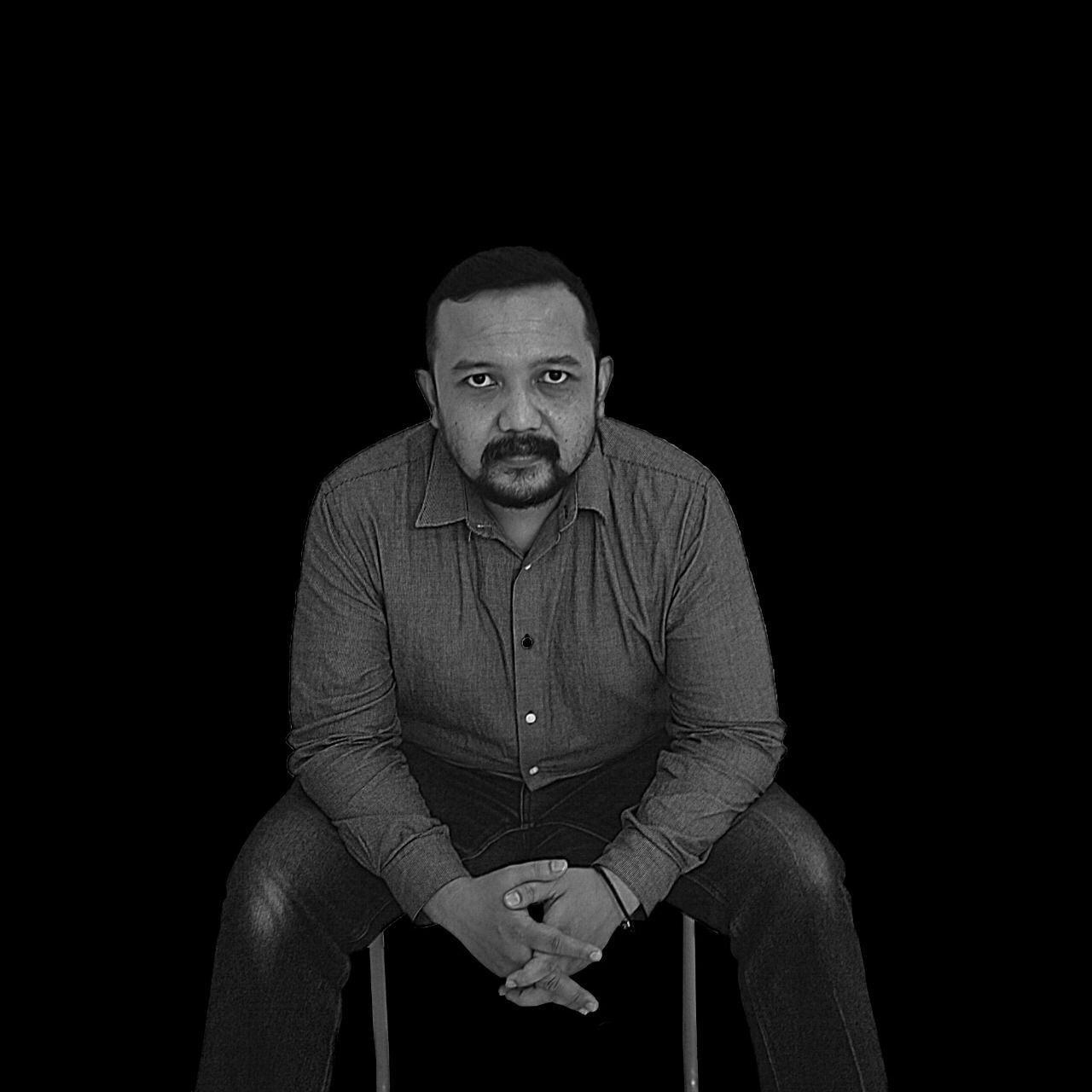Oleh: Riswanda
Catatan Riswanda berkenaan gentingnya tindak kekerasan seksual di Indonesia tertulis di ‘Mempertikaikan RUU PKS’ (Banten Raya 2021, 9 Oktober).
Januari lalu, sidang paripurna hanya bersifat pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR RI. Menyimak kembali coretan Riswanda dalam ‘Keniscayaan hadirnya UU TPKS’ (Banten Raya 2022, 17 Januari), pemerintah dalam hal ini Kemen PPPA telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
Sepertinya, Surat Presiden (Surpres) perihal TPKS akan dilayangkan dalam minggu ini atau minggu depan sebelum reses. Berdekatan dengan momentum perayaan hari kasih sayang, atau lebih dikenal dengan valentine.
Sorotan Riswanda kali ini akan mengupas celah lain ketepatan sangkala bagi sebuah kebijakan untuk disampaikan pada publik. Bukan hanya sekadar sosialisasi konvensional tentunya, tapi lebih pada diskursi ketepatan siasat sampainya usungan pesan dari sebuah regulasi pada calon kelompok sasar.
Kenapa justru hari kasih sayang disangkutpautkan dengan TPKS? Mungkin sudah hilang dalam benak publik, bahwasanya kejadian-kejadian kekerasan seksual marak di hari valentine. KPAI (2016, 12 Februari) sempat menyorot pariwara penginapan bagi pasangan muda berkemas perayaan valentine. Cokelat berhadiah kontrasepsi, dianggap memfasilitasi anak usia sekolah berpotensi menjadi pelaku, atau bahkan korban kejahatan seksual. Tajuk pemberitaan seperti ‘kejahatan seksual marak saat hari valentine’, ‘tingkat kekerasan seksual saat valentine tinggi’, atau ‘kampanye stop kekerasan seksual saat valentine’ ramai mengisi pemberitaan media (Merdeka 2015, Republika 2015, Liputan6 2015). Lebih kurang dua dekade ke belakang.
Kenapa ihwal TPKS dapat disebut sebagai timeless issue? Atau permasalahan yang tidak lekang termakan waktu. Lebih sentral lagi, sejauh mana gapaian tangan kebijakan publik dapat memperbaiki situasi, dan bukan semata-mata formalitas respon? Sudah menjadi hasil kajian bahwa kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja, terlepas latar belakang agama, relasi sosial dan cara berpakaian. Banyak faktor disinyalir sebagai pemicu.
Meskipun, bahasan khusus diperlukan konteks Indonesia. Warna budaya ketimuran dan corak patriarkal dua diantaranya. Pijar ungkap kasus kekerasan seksual ke ragam ruang media sosial, menyiratkan pesan baru sebetulnya.
Yaitu bagaimana pilar penafsiran regulasi kebijakan mengentaskan stigma lapuk proses keadilan bagi korban.
Hasil kontradiktif jalur pengaduan dan pelaporan korban condong terjadi pada pilihan korban untuk diam. Eksposur media mengulas kasus tertentu dimana aneka tingkat pelanggaran dan bentuk kekerasan, seolah justru melindungi pelaku dan menyudutkan korban. Aduan berbalik tuduhan.
Bahasa kekuasaan tidak membantu. Nomenklatur budaya bersifat timeless dan kemungkinan menghasilkan frasa perubahan ke arah perbaikan. Keputusan karbitan khawatir mengarah pada solusi parsial, segmental, katakanlah setengah-setengah secara sederhana.
Padahal, keterpaduan langkah aksi dibutuhkan pecahan beda bidang kerja selama ini. Semisal, memperpadukan aspek pemulihan dengan penindakan. Kuncinya terletak pada derap turunan program-program. Aksi seharusnya berbaju lurus penafsiran terhadap upaya menghapuskan kekerasan seksual. Maksudnya, silaturahmi pemikiran harus terjalin lebih dulu.
Betul bahwa RUU TPKS telah menggolongkan sembilan bentuk kekerasan seksual yaitu perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pernikahan paksa, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan aborsi.
Hanya saja rezim administratif harus legowo dengan kondisi khusus yang mungkin dialami penyintas. Dalam arti, pemahaman kebijakan turut menyertakan solusi kerentanan penyintas ketika berhadapan dengan dampak poleksosbud. Kebolehjadian mengidap penyakit seksual menular dan Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) cukup jelas.
Belum lagi ditambah kemungkinan stigma buruk di lingkungan sosial. Seakanakan penyintas ternilai pelanggar nilai kesusilaan. Socially excluded, tersisihkan secara sosial dapat memperparah kondisi psikologis penyintas. Kalau begitu, jalan keluarnya seperti apa? Mengudarakan pencegahan salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan moment valentine.
Memicu kontemplasi bagaimana ungkapan kasih sayang, ikut menjadi instrumen pencegah terjadinya tindak kekerasan sesual. Kemen PPPA-BPS (2016) merilis data, 34,4 persen kekerasan seksual paling banyak dialami perempuan yang belum menikah. Mayoritas pelaku mengarah pada individu yang secara relasi sosial akrab korban, semisal kekasih, kolega, atau tetangga.
Tercatat, sebanyak 2.090 dari 10.847 pelaku kekerasan terkategori pacar atau teman (Simfoni PPA 2016). Mengudarakan pencegahan, sehaluan mendaratkan penindakan, dapat dimulai dari menentukan lebih dulu core values (nilai inti) perundangan TPKS. Selanjutnya, people first then what atau siapa bakal eksekutor di lapangan, kapasitas pelaksana, termasuk karakteristik sosial-budaya pelaksana.
Baru kemudian apa saja esensi strategi kebijakan tersebut. Inovasi, penyintas yang telah pulih digandeng serius formal menjadi aktor untuk melakukan social mapping (pemetaan sosial). Lived experiences (pengalaman hidup) penyintas siapa tahu berharga sebagai pendalaman evaluasi upaya-upaya eksisting meniadakan kekerasan seksual.
Penulis adalah Akselerator Kebijakan Associate Professor Analisis Kebijakan UNTIRTA