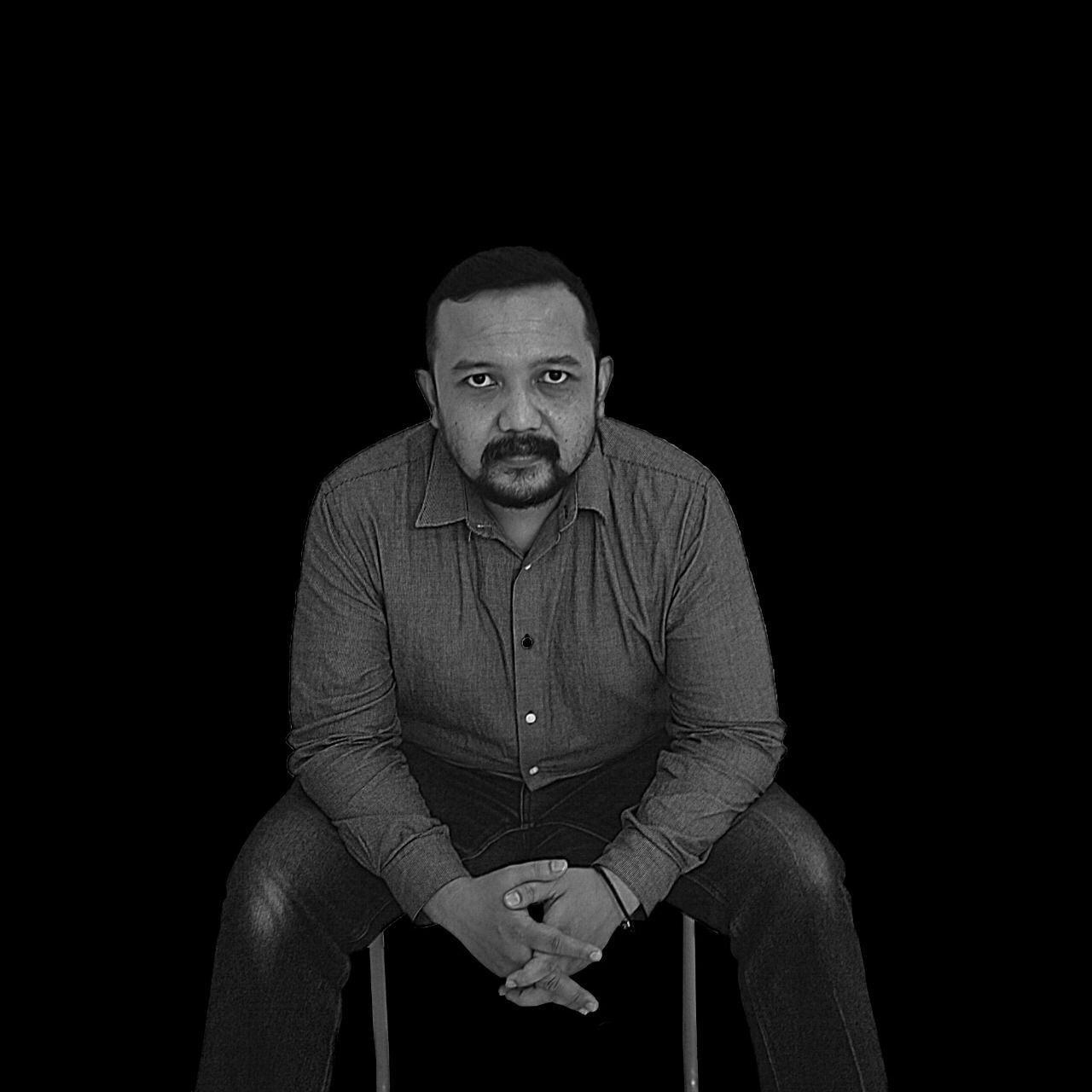Oleh: Riswanda PhD
Runtutan regulasi kebijakan publik menyoal isu perlindungan anak telah digulirkan pemerintah Republik Indonesia. Pokok pikiran untuk menubuhkan perencanaan dan langkah aksi nasional melindungi anak dari tindak kekerasan, serius dimulai oleh Inpres 5/ 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
Inpres menggandeng khusus lintas Kementerian dan Lembaga, menuntun unsur POLRI serta kepala daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berbasis komunitas.
Kehadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Perpres 61/ 2016, mempertegas perisai nasional di tema ini. Lebih lanjut, Perpres 65/ 2020, menyambut penekanan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, bagian dari bidang kerja Kedeputian Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA. Perpres 25/2021 berkenaan Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak anak mestinya segaris dengan PP 78/ 2O2I mengenai perlindungan khusus bagi anak. Artinya, sorotan kebijakan pada ranah ini cukup menyentuh frasa kunci.
Masih mencuatnya kasus kekerasan pada anak adalah fakta memelikkan. Catatan Hari Anak Nasional (Kompas 2021, 23 Juli) melansir 5.463 anak masih mengalami kekerasan, dan bahkan menukil angka sebaran pada 10 wilayah Provinsi yang memiliki angka kasus kekerasan paripurna.
Merujuk laporan Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 3 Juni di tahun berjalan, MediaIndonesia (2021, 5 Juni) mencatat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak. Biro Data dan Informasi Kemen PPPA mewartakan 3.683 anak menjadi korban kekerasan dalam rentang waktu Januari-Juni (Paudpedia.kemdikbud 2021, 5 Juni).
Kendatipun di sini kesimpangsiuran angka relatif tampak, mungkin ada baiknya bagi sebuah intervensi kebijakan untuk juga mengkaji kedalaman masalah.
Pencarian akar dari akar-akar permasalahan yang mungkin kasatmata di permukaan, sebagai policy problem, dapat menjadi frasa kunci baru di kajian Kota Layak Anak.
Penyelesaian masif memang perlu, lebih cakap lagi jika kedalaman bidikan solusi menjadi bekal ancangan regulasi. Pertanyaannya kemudian, mungkinkah menihilkan kekerasan pada anak? Jawaban pertanyaan ini tentunya memerlukan insights khusus. Ragam stresor lingkungan bisa saja mendorong terjadinya tindak kekerasan, termasuk pada anak.
Investasi terbanyak seharusnya diberikan pada upaya-upaya pencegahan pada pranata sosial dimana anak paling sering berada, yaitu lingkungan pendidikan (sekolah) dan lingkungan keluarga. Kenapa begitu? Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR 2018, Kemen PPPA 2019) menyuguhkan ulasan data yang cukup menarik, bahwa 70 persen dari pelaku kekerasan fisik, emosi, dan seksual terhadap anak adalah teman atau sebaya. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana menempatkan kedalaman cetak biru antisipasi-solusi kebijakan dalam hal ini?
Pertama, mendaratkan strategi kebijakan nasional dapat ditempuh dengan memastikan daerah memenuhi kewajiban menyusun petunjuk pelaksanaan di masing-masing satuan tugas. Permen PPPA 8/ 2014 menyoal Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sebuah terobosan penting. Sambutan positif muncul melalui Perwali dan Perbup di beberapa wilayah Kabupaten/ Kota.
Apik, jika Permendikbud mengawal leburan slogan ini di tataran pelaksanaan. Melebur pelaksanaannya dengan penyelenggaraan pendidikan adalah bijak. Masa kebiasaan baru sepertinya memberi hikmah penyelenggaran webinar, berikut filosofi ‘kemerdekaan belajar’ (Riswanda 2021, Banten Raya, 17 Agustus).
Webinar series dapat mengupas kemungkinan minimnya rasa empati dalam diri anak-anak, yaitu kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik.
Webinar bertema menumbuhkan rasa empati pada anak sejak dini, taruh kata, dapat menjadi awalan sederhana untuk disinambungkan dengan program-program eksisting. School bullying dan tayangan tak ramah anak adalah dua diantara banyak tema yang memerlukan tindak lanjut pendalaman kajian.
Kedua, kemunculan slogan-slogan baru untuk kemudian dibaca sebagai program baru, katakanlah inovasi, hendaknya dikaitkan dengan strategi berjalan. Ukuran keberhasilan SRA perlu dirantaikan dengan lima klaster Hak Anak di program bergerak Kota Layak Anak, diantaranya Klaster ‘pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif’, serta Klaster ‘pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya’.
Maksudnya adalah agar jangan sampai eksekutor di daerah hilang fokus pendalaman. Gagap memunculkan slogan baru bisa berubah menjadi tafsiran baru atas slogan sebelumnya. Mendalami penerapan strategi dapat juga dilakukan dengan tidak terkungkung pada satu aspek persoalan.
Karena bisa jadi antisipasi-solusi kebijakan menyorot aspek yang saling terkait dengan aspek lain — sistemik. Seumpama, bagaimana daerah memastikan terpenuhinya hak anak-anak berkategori ‘memerlukan perlindungan khusus’, diperlukan akselerasi kebijakan multi-jenjang melalui pendalaman kritis-konstruktif (Riswanda, critical policy analysis 2008, 2018).
Penutup, slogan baru tidak cukup hanya senada. Lebih penting, bagaimana membuat mereka seirama dan satu frekuensi dalam menetapkan tolak ukur capaian keberhasilan. Termasuk penentuan mata (silang) anggaran, evaluasi keberlanjutan dan arah bobot prioritas, Kebaruan bukan berarti menandai program dengan slogan baru. Menyegarkan langkah aksi juga dapat dilakukan lewat pendalaman perihal apa yang memunculkan tantangan, hambatan dan pemetaan peluang perbaikan ke depan.
Penulis adalah Associate Professor — Akselerator Kebijakan