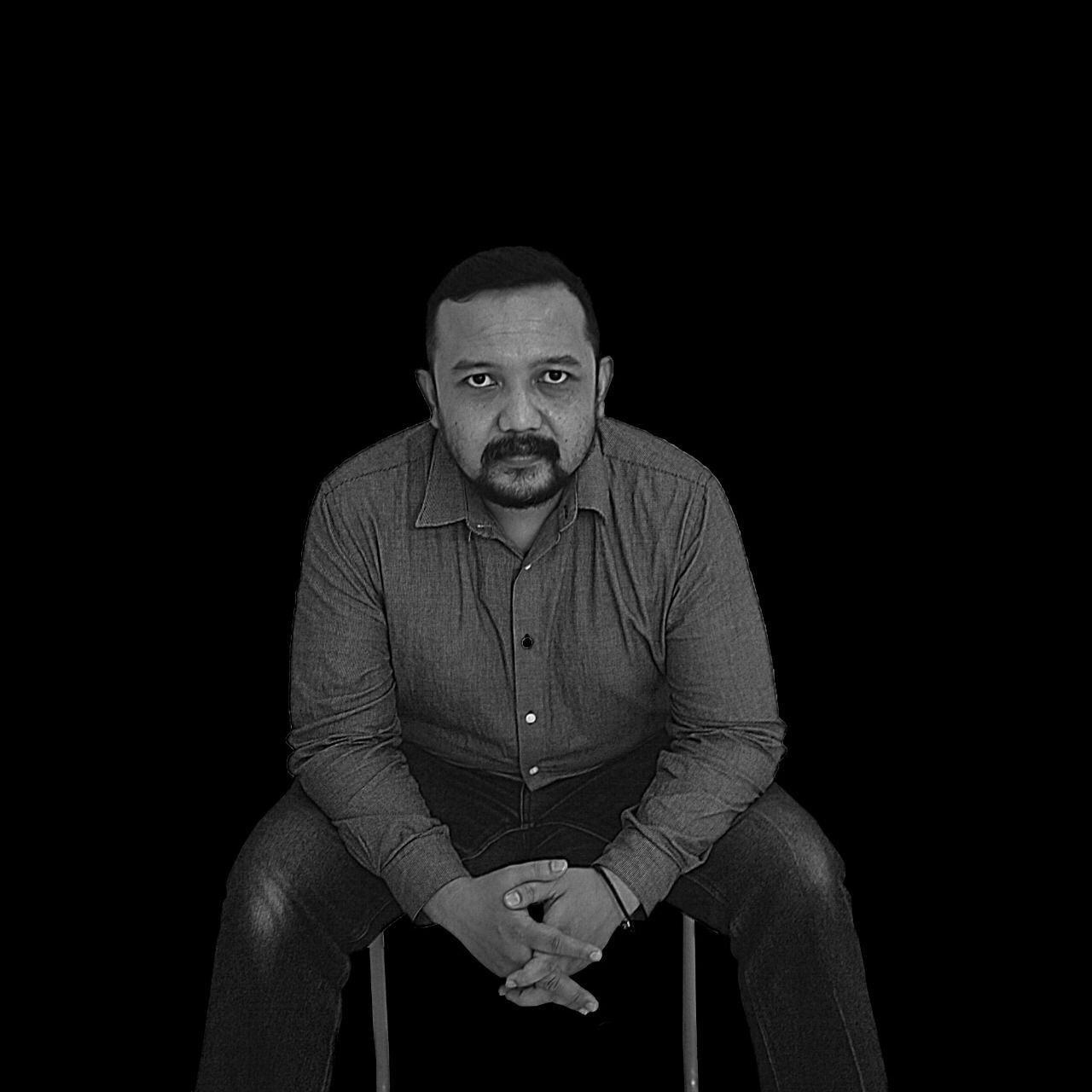Oleh: Riswanda PhD
Menilik pengejawantahan di masa lampau, sebutan negara agraris bagi Indonesia bukan sekadar cakap angin.
Negeri ini diakui dunia mencapai swasembada pangan. Perhelatan Konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization (FAO), 14 November 1985, Nusantara menyumbang 100.000 ton bagi korban kelaparan di sejumlah negara Afrika.
Kendatipun, prestasi membanggakan ini terancam sirna. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meramalkan lenyapnya profesi petani di Indonesia pada tahun 2063 (Kompas 2021, 23 Maret).
Renungan ini dihasilkan dari tren lonjakan pekerja sektor industri, yaitu 22.45 persen (2019) dibandingkan 8,86 person (1976). Kemerosotan angka lahan pertanian ikut andil menandai gentingnya persoalan ini.
Kurun waktu 2013-2019 saja, terjadi pengurangan 0,3 hektar, diprediksi terus naik seiring masifnya alih fungsi lahan pertanian dan singgungan dampak urbanisasi.
‘De-generation of farmers’ atau putusnya generasi petani (Riswanda 2018) merupakan isu sistemik, memanggil ruang kaji ilmiah. Kecakapan antisipasi-solusi kebijakan diperlukan.
Merujuk lansiran data Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian (Kementan RI 2021), prosentase tenaga kerja pertanian dan non-pertanian terhadap total tenaga kerja Indonesia adalah 29,58 persen berbanding 70,41 persen.
Perangkaan yang cukup mengkhawatirkan sebetulnya, mengingat tren gelombang urbanisasi ke kota-kota besar terus meningkat tajam (BPPN BPS 2013).
Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 mencatat, terhitung satu dekade gelombang urbanisasi ke Jakarta mencapai 100 persen, dengan kata lain telah mencapai batas daya tampung kota.
Urbanisasi sepertinya dilakukan tenaga kerja produktif usia muda perdesaan yang ingin memperbaiki taraf ekonomi mereka.
Termasuk alasan mengincar potensi penghasilan lebih dan cepat, yang memang umumnya ada di lingkup perkotaan. Hamid, Riswanda, Widyastuti (2018) mengingatkan bahwa tren ini bisa juga terjadi di wilayah perdesaan itu sendiri, dimana profesi petani tidak lagi dipandang menjanjikan baik secara ekonomi maupun status sosial.
Pelawaan Presiden Joko Widodo agar Kementerian terkait mendororong minat generasi muda untuk menggeluti profesi petani tepat adanya. Pengukuhan duta petani milenial (CNBC Indonesia 2021, 6 Agustus) termasuk terobosan. Kenapa begitu? Tercatat dominasi 71 persen petani Indonesia berada pada rentang usia 45 tahun ke atas, sementara petani berkategori di bawah umur 45 tahun hanya 29 persen.
Slogan ‘tinggal di desa, rejeki kota, bisnis mendunia‘ bahkan menjadi langkah aksi petani milenial di Jawa Barat (Ridwan Kamil, Injabar UNPAD 2021), melibatkan 500 anak muda Jawa Barat dan 2000 meter persegi lahan pertanian.
Artinya, konsepsi dan pengembangan ruang kerja ilmiah ketahanan pangan jangan sekadar mengusik ruang khusus agrikultural.
(Riswanda, dkk 2021) menekankan pentingnya penafsiran ulang jargon ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Aspek sosial-politik seringkali dianggap minor memadankan gatra teknis olah pangan.
Padahal, kondisi terus berkurangnya pekerja di sektor pertanian dari masa ke masa, katakanlah dari generasi ke generasi, menghajatkan sorotan kebijakan publik. Program pemulihan minat generasi muda untuk bekerja ataupun melanjutkan ‘legacy’ petani, mesti diiringi dengan kemauan politik konsekuensial mengatasi pejalnya alih fungsi lahan di negeri ini.
Tersisip strategi mengukur keberlanjutan pengentasan kesenjangan ruang spasial perkotaan – perdesaan.
Sehingga kelompok sasar dari langkah aksi re-generasi petani, sebagai ‘antidote’ de-generasi petani, tidak menganggap slogan anyar sebagai anekdot. Melainkan, ‘professional farmers’ dapat menjadi ukuran karier segagasan dengan profesi idaman lain.
Penulis adalah akselerator kebijakan, Associate Professor bidang Analisis Kebijakan FISIP UNTIRTA