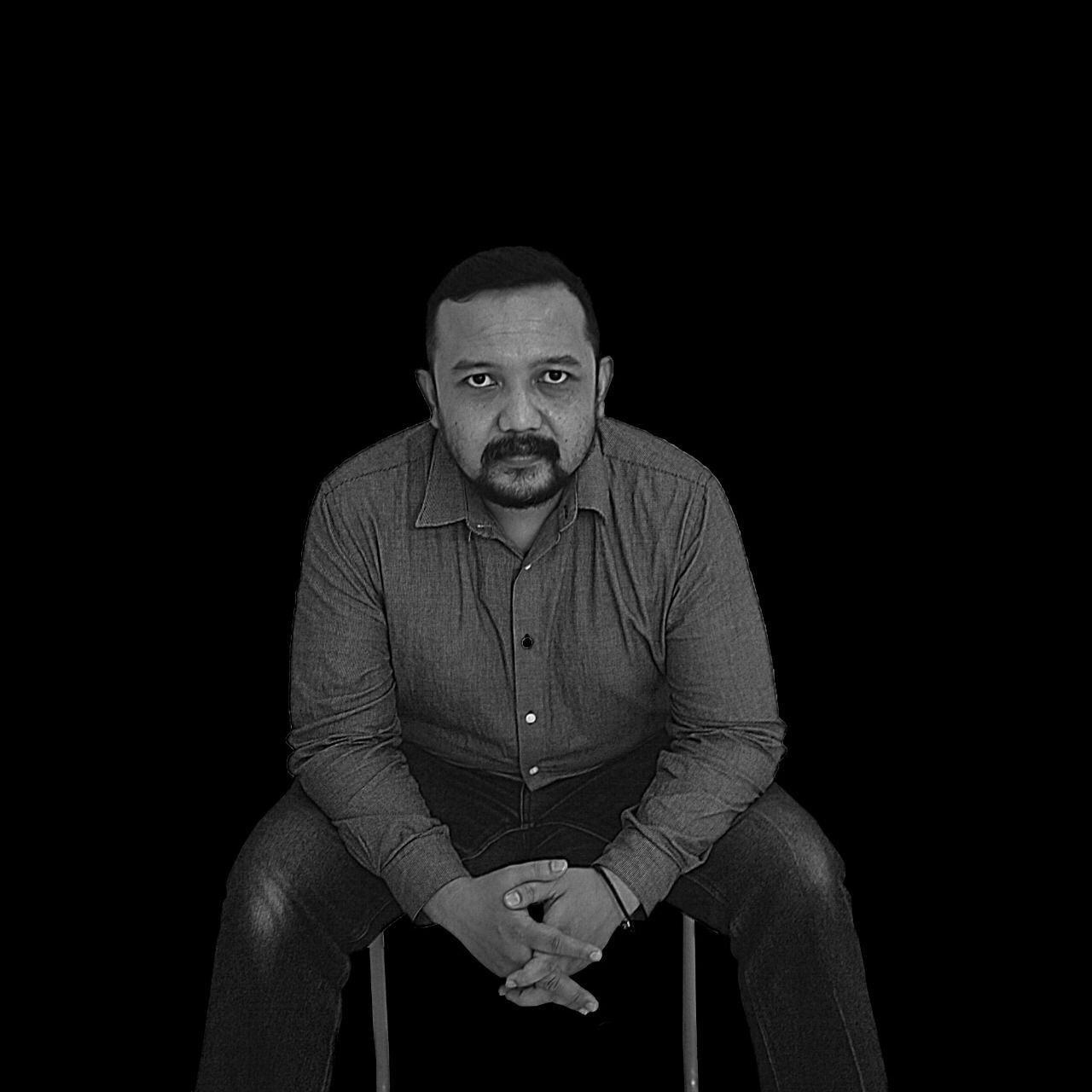Oleh: Riswanda
Era hyper-connected memanggil insan berdaya saing unggul. Hiperkonektivitas sering diartikan sebagai penggunaan pancawarna sistem dan perangkat yang dapat menjejaringkan sumber informasi bagi penggunanya. Konektivitas internet menjadi kunci sosial keterhubungan antar invidu, dan berimbas pada pola interaksi antar lembaga.
Kelembagaan kerja adalah salah satu penerima imbas. Pemahaman populer ‘revolusi industri 4.0’ berikut sembilan pilar usungan jargon ini mencuat dalam diskusi ketenagakerjaan. Lingkup diskusi dimana sektor tenaga kerja menjadi sorotan lebih. Mengapa begitu?
Pertama, sedikitnya enam dari kesembilan pilar ‘revolusi industri 4.0’, bukan sekedar jargon kosong. Internet of things, cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, super apps dan broadband infrastructure berdampak serius pada tipe kebutuhan tenaga kerja.
Tenaga kerja tanggap digital dapat dengan mudah menggeser pasaran pekerja konvensional. Tentu saja pemahaman keterampilan digital tidak terbatas pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Riswanda (2020, KORAN SINDO, 2 September) menekankan keterampilan multi-tasking sebagai kebutuhan primer diskursi ketenagakerjaan, ‘melecut penciptaan lapangan kerja yang berkualitas sebanyak 2,7 sampai 3 juta per tahun’ adalah haluan bersama.
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 122 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021, mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, tepat mengisi diskursi ini. Prioritas Nasional 3, ‘Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing’ semestinya menggarisbawahi matriks pengaktualan program kerja pemerintah di situasi pandemi COVID-19. Penciptaan lapangan kerja baru berkualitas secara mahardika, sebenarnya mampu meyepadankan program pemulihan ekonomi dengan penanganan dampak pandemi.
Kedua, kompleksitas dunia kerja kontemporer sepertinya melabelkan kemewahan bagi pekerja untuk bisa nyaman mengerjakan satu saja jenis pekerjaan dalam satu waktu. Pada banyak tipe pekerjaan kekinian, pemberi kerja biasanya memilih pekerja yang sanggup menangani multi-prioritas sekaligus.
Semakin kompetitif ketersediaan lapangan kerja, menyempit pula pilihan bagi pekerja untuk tidak ikut menyesuaikan keterampilan dan kesanggupan multi-tasking. Kecakapan merotasikan pikiran dan konsentrasi dari satu aktivitas kerja ke aktivitas lain, disambi kemampuan memilah mana yang harus didahulukan berdasarkan bobot prioritas, bisa dikatakan penjelasan sederhana dari multi-tasking skills. Jadi, cukup jelas bahwa keterampilan mutakhir justru lebih pada ukuran andal berpikir dibanding hanya sekedar melek digital.
Ketiga, jika saja critical thinking skills dapat diadapsi pada tiap jenjang kelembagaan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan, maka mimpi menciptakan spesialis unggul di bidangnya bukan mustahil terwujud.
Critical thinking (berpikir kritis) dapat dipahami sederhananya sebagai melihat dan memahami sesuatu hal secara keseluruhan, dan mengungkap keterhubungan di antara perlbagai hal yang mungkin sekilas tampak berlainan (Riswanda 2021, Bab Critical thinking, Handbook Filsafat dan Logika, UPNVJ).
Kemampuan menjelaskan dan menarik ‘benang merah’ di antara beragam aspek yang bisa saja saling berhubungan tadi merupakan salah satu cara berpikir kritis. Terminologi berpikir kritis sering ditafsirkan keliru sebagai kemampuan menyampaikan kritik, bahkan bisa jadi oleh sebagian orang secara keliru diartikan menjadi pencarian kesalahan dari ide-ide ataupun karya orang lain.
Padahal, berpikir kritis melibatkan pencarian pemahaman mendalam terhadap informasi tertentu untuk kemudian menghasilkan kesimpulan berbasiskan bukti-bukti ilmiah. Utamanya jika Kita berada pada lingkungan akademis. Hubungannya dengan ketenagakerjaan? Usungan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 3/ 2020, dapat pula dikaji kembali irisan keterhubungannya dengan pendidikan dasar dua belas tahun.
Bagaimana dengan misalnya ‘Merdeka Belajar – Sekolah Merdeka’? Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat, ciptakan ‘pembelajar sejati’, adalah tepat. Lebih lagi, menjembatani kajian-kajian akademis dengan permasalahan aktual-faktual di dunia nyata adalah kunci kedekatan konsepsi pendidikan dengan realitas hidup keseharian.
Meskipun, reka cipta ‘pembelajar sejati’ perlu sebangun dengan pijakan wadah pendidikan sebelumnya. Kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah juga harus senada. Jangan sampai menu pokok ‘calon generasi unggul tanggap lapangan kerja’ Indonesia dipenuhi oleh kursus, bimbingan belajar, dan bimbingan keterampilan, dikarenakan kualitas pembelajaran di sekolah yang mungkin masih cenderung mencetak pola pikir peserta didik sebagai memori komputer dibanding wadah kritis berkreasi.
Pekerjaan seharusnya bukanlah hasil, tapi lebih kepada sarana mencapai hasil itu sendiri. Pekerja yang paham tujuan menyelami dan mendalami sebuah perkerjaan, akan cenderung menghasilkan produk kerja autentik.
Sehingga spesialisasi tidak diartikan sebagai kelatahan memperoleh sertifikat, tapi lebih kepada capaian kemampuan berpikir. Proses invensi manusia pemikir adalah outcome dari luaran menghasilkan SDM unggul berkualitas, dan bukan penataan robot pekerja berkemampuan pikir statis.
Penulis adalah Associate Professor — Akselerator Kebijakan